Nama “Mbah Petruk” mendadak menjadi terkenal ke seantero negeri pasca letusan Merapi yang mewarnai November 2010 bak selebritis baru yang sedang menanjak karirnya . Apalagi setelah salah seorang warga bernama Suswanto, 43 tahun, berhasil memotret asap solvatara gunung Merapi yang menyerupai kepala Petruk. Selama ini mitos Mbah Petruk sering dikaitkan dengan pemuka jin ini bertugas memberi wangsit mengenai waktu meletusnya Gunung Merapi, termasuk juga memberi kiat-kiat tertentu kepada penduduk agar terhindar dari ancaman bahaya lahar panas Merapi. Dipundak jin inilah, menurut isu yang sempat beredar, keselamatan penduduk tergantung.
Tentu saja tanggapan atas mitos Mbah Petruk cukup beragam. Jika ilmuwan vulkanologi menyatakan awan mirip Petruk tidak berarti apa-apa, Ponimin (50) yang disebut-sebut “sakti” seperti Mbah Maridjan, punya penafsiran sendiri. Menurutnya, hidung Petruk yang menghadap Yogyakarta mengandung arti Merapi mengincar Yogyakarta. (detiknews,13/11/2010). Permadi, seorang paranormal, dalam sebuah infotainmen “Silet” di sebuah televisi siaran swasta nasional memiliki pendapat yang hampir serupa dengan Ponimin. Lain lagi dengan Sultan Hamengkubuwana, Gubernur Yogyakarta saat ditemui di Kepatihan (2/11/2010) mengungkapkan: “ Itu kan kata mereka. Kalau aku bilang itu Bagong, bagaimana? Atau itu Pinokio, karena hidungnya panjang”. (Tempointeraktif.com, 2/11/2010). Spekulasi terus bermunculan akibat photo ini. Belum lagi juga muncul photo lain dari asap Merapi yang membentuk tulisan Arabic “Allah”.
SIAPAKAH MBAH PETRUK ?
Tidak diragukan bahwa nama Mbah Petruk telah menjadi sebuah mitos yang tidak terpisah dari warga yang mendiami wilayah sekitar Gunung Merapi. Tokoh ini sering dikaitkan sebagai penguasa gaib Merapi yang “bertanggungjawab” terhadap dunia “gaib” Merapi. Cerita tentang “kekuasaan” Mbah Petruk” ini secara umum berkembang di sekitar lereng Merapi terutama di wilayah yang masuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat Cepogo dan Selo yang menjadi “basis kerja” Mbah Petruk pada “masa lalu” justru memiliki versi yang cenderung berbeda.
Berdasarkan cerita Versi warga Cepogo bagian atas, nama asli Mbah Petruk sebenarnya adalah Kyai Handoko Kusumo. Kyai Handoko ini merupakan penyebar Islam di Merapi pada sekitar era 1700-an. Wilayah geraknya lebih banyak meliputi Cepogo bagian atas dan tidak menutup kemungkinan juga di wilayah yang lain. Dalam cerita tutur digambarkan bahwa ia memiliki bentuk badan yang agak bungkuk. Kyai Handoko Kusumo adalah seorang keturunan Arab. Bentuk hidungnya yang lebih mancung dari kebanyakan orang Jawa itulah yang membuat dirinya dikenal dengan nama Mbah Petruk oleh Masyarakat setempat. Petruk dalam mitologi Jawa merupakan tokoh wayang punakawan yang memiliki bentuk hidung sangat mancung. Meskipun demikian menghubungkan Mbah Petruk dengan tokoh pewayangan Petruk jelas merupakan sebuah kekeliruan.
Mbah Petruk ini adalah seorang ulama yang dimungkinkan merupakan murid generasi kedua dari Sunan Kalijaga. Sebagai seorang ulama ia memiliki level setingkat ulama lain yang semasa dengan kehidupannya seperti Mbah Ragasari yang dimakamkan di Tumang dan juga dai yang lain bernama Hasan Munadi. Juru kunci Merapi pada era Mbah Petruk ini bernama Kyai Rohmadi, seorang muslim pula, yang oleh penduduk setempat dikenal dengan nama Mpu Permadi. Hanya saja agak berbeda dengan Mbah Petruk, Mpu Permadi memiliki gaya keislaman yang lebih dekat dengan dunia klenik, terutama pengamalan terhadap kitab Mujarobat (semacam primbon). Mpu Permadi ini nampaknya telah terpengaruh dengan mistisme Persia yang bersumber dari kitab Syamsul Ma’arif Kubro yaitu sebuah kitab yang menggabungkan dunia perdukunan Persia dan mistisme Syiah. Kitab ini boleh dikatakan sebagai sumber dari hampir semua kitab Mujarobat yang banyak beredar di masyarakat. Isinya berupa kumpulan mantra, penggunaan azimat, wifiq, dan lain sebagainya. Makam Mpu Permadi dapat ditemui di Watu Bolong.
Dalam versi masyarakat Selo, Mbah Petruk seringkali disebut-sebut sebagai anak seorang pejabat atau versi lain Wedana. Pada era ini Selo merupakan wilayah dari kawedanan Ampel yang membawahi Ampel, Cepogo, Paras, dan Selo. Versi ini tidak bertentangan dengan versi cerita cerita warga Cepogo. Hal ini tidak mengherankan, sebab salah satu fenomena penyebaran Islam adalah melalui perkawinan, termasuk membangun kedekatan dengan menikahi putri-putri penguasa setempat. Namun demikian secara umum, masyarakat sekitar Merapi telah mafhum bahwa Mbah Petruk merupakan salah seorang penyebar agama Islam di sekitar daerah itu. Pada masa tuanya, Mbah Petruk diperkirakan meninggal di Gunung Bibi dan jasadnya tidak pernah diketahui. Hal inilah yang memunculkan anggapan spekulatif bahwa dirinya telah moksa. Perlu diketahui Gunung Bibi sampai hari ini masih merupakan kawasan “berbahaya” karena masih dihuni hewan-hewan liar termasuk oleh ular-ular python raksasa. Tidak mengherankan jika penduduk sekitarnya selalu menahan KTP para pendaki yang hendak naik ke Gunung Bibi, alasannya agar bisa segera memberitahu keluarganya bila pendatang yang bersangkutan tidak kembali turun dari gunung. Fenomena ini bisa saja menjelaskan hal tersebut disamping adanya kemungkinan lain yang logis.
TANTANGAN DAKWAH MBAH PETRUK
Sesuai dengan pendapat Karel Steenbrink, sampai sekitar tahun 1700-an, daerah di sekitar Merapi masih merupakan kawasan yang penduduknya menganut Agama Hindhu. Namun catatan yang lain menyebutkan bahwa pada era Perang Jawa (1825-1830), ulama dan sekaligus penasihat spiritual Pangeran Diponegoro yang bernama Kyai Mojo telah memobilisasi pasukan yang berasal dari lereng Merapi. Hal ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi di kawasan ini telah berjalan.
Pada era awal dakwah di lereng Merapi, tantangannya tidaklah mudah. Aliran yang berkembang di lereng Merapi pada masa ini menunjukkan adanya sinkretisme antara agama Kapitayan dan aliran Bhairawa Tantra. Di Jawa aliran ini memang telah menyatu dengan mantra-mantra Jawa Kuno dan kepercayaan terhadap para tukang tenung. Penobatan raja-raja Jawa dilakukan melalui percampuran ritual tantra disertai dengan berbagai sihir dan ajaran rahasia. (Prijohutomo, II, 11953: 105).
Agama Kapitayan adalah keyakinan masyarakat Jawa sebelum proses Indianisasi yang meliputi perkembangan agama Hindhu dan Budha. Ajarannya yang hanya mengenal satu Tuhan memiliki sejumlah kemiripan dengan monotheisme. Ritualnya adalah menyembah Hyang Taya yaitu pencipta alam semesta yang memiliki sifat tan kinaya ngapa (tidak dapat diperkirakan oleh akal pikiran manusia). Ibadahnya disebut sembahyang dilakukan sebanyak 3 waktu dalam sehari yaitu saat matahari terbit, matahari diatas kepala, dan matahari terbenam. Kepercayaan ini memiliki tempat peribadatan yang bangunan berbentuk segi empat bernama langgar. Untuk memasuki langgar seorang penganut Kapitayan harus dalam keadaan bersih dan melepas alas kaki yang dikenakannya. Dalam Kapitayan sendiri terdapat dua cara pandang yang saling berbeda yaitu Tu dan To. Penganut pandangan Tu melakukan ritual agamanya dengan tanpa perantaraan (tawasul). Mereka menyembah penciptanya dengan mengandalkan ketaatan diri kepada pencipta dan tanpa membutuhkan wujud materi yang digunakan untuk sesaji. Sedangkan penganut pandangan To membutuhkan persembahan berupa sesaji dalam rangkaian peribadatannya. Dalam mitologi pewayangan Jawa karakter berpandangan Tu diejawantahkan dengan Semar Badranaya yang menjadi pamomong para satriya berwatak mulia. Sedangkan karakter To dengan disimbolkan dengan tokoh Togog yang menjadi pamomong para bhuta dan danawa yang berwatak candala.
Sedangkan Bhairawa Tantra merupakan bentuk sinkretisme dari Siwa-Budha. Awalnya keyakinan ini hanya berkembang di elit politis Keraton Jawa saja dan berfungsi untuk menjaga kewibawaan penguasa. Cara pandang utama dari aliran ini adalah dengan memperturutkan hawa nafsu maka kecenderungan jiwa pada akhirnya akan lebih mudah diarahkan untuk menjauhi nafsu-nafsu tersebut. Menurut ajaran ini, orang hendaknya jangan menahan nafsu, bahkan sebaiknya manusia itu memperturutkan hawa nafsu. Sebab bila manusia terpuaskan nafsunya, maka jiwanya akan menjadi merdeka. (Prijohutomo, I, 1953: 89). Bentuk ritualnya meliputi apa yang dikenal dengan sebutan ma-lima atau pancamakara. Ritual Ma-lima tersebut terdiri dari matsiya (ikan), mamsa (daging), madya (minuman keras), mudra (ekstase melalui tarian yang terkadang bersifat erotis atau melibatkan makhluk halus hingga “kerasukan”), dan maithuna (seks bebas). (Rasjidi, 1967: 68; Soekmono, 1988: 33-34). Dalam bentuk yang paling esoterik, pemujaan yang bersifat Tantrik memang memerlukan persembahan berupa manusia. Ritualnya meliputi persembahan berupa meminum darah manusia dan memakan dagingnya. (Munoz, 2009: 253, 448). Juga ritual seks bebas dan minum minuman keras yang dilakukan ditempat peribadatan berupa lapangan (padang) bernama Lemah Citra atau Setra. Ritual tersebut dilakukan untuk mendapatkan cakti. Oleh karena itu aliran ini juga sering disebut sebagai saktiisme. Pada era selanjutnya dapat dijumpai sisa-sisanya dalam apa yang disebut dengan istilah kasekten. (Koentjoroningrat, 2007:347).
Proses Indianisasi di Pulau Jawa dengan produk berupa Hindhuisme dan Budhisme memang memberi nilai tambah dalam bidang teknis seperti arsitektur dan seni, namun bersifat destruktif terhadap keyakinan awal masyarakat Jawa yang telah monotheis. Kasus serupa juga terjadi di Sunda, Kidung Jatiniskala telah menunjukkan bahwa masyarakat Sunda Kuno telah memiliki kecenderungan kepada kepercayaan terhadap Sang Pencipta yang mirip konsepsi Tauhid dalam Islam. Belum lagi jika kita mau meneliti lebih lanjut terhadap Agama Sunda Wiwitan.
Salah satu wujud ritual yang terpengaruh oleh pembauran antara Agama Kapitayan yang bersifat To dan Bhairawatantra yang dijalankan di Merapi adalah pengorbanan manusia untuk menolak mara bahaya dan bencana. Pengorbanan ini dilakukan dengan menceburkan manusia ke dalam kawah Merapi. Bentuk pengorbanan dengan menggunakan manusia ini sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Bhairawatantra yang merupakan sinkretisme antara Hindhu dan Budha ini. Bentuk pengorbanan yang hampir sama masih kita jumpai dalam tradisi tutur yang berkembang di sekitar Gunung Bromo. Di Gunung Bromo juga terdapat tradisi mempersembahkan hasil bumi ke kawah Bromo yang merupakan perkembangan dari ritual ini. Berdasarkan tradisi tutur pula dapat diketahui bahwa penduduk Gunung Bromo sebenarnya merupakan pelarian dari Majapahit, sebuah kerajaan Jawa Hindhu-Budha yang bercorak Bhairawatantra.
Pada era dakwah Mbah Petruk bentuk pengorbanan ini mulai diperhalus dengan menggantinya dengan kepala kerbau. Kepala kerbau tersebut di tanam di Pasar Bubrah yang merupakan puncak Gunung Merapi Purba dan juga dimasukkan ke kawah Merapi. Tentu saja proses subsitusi korban manusia dengan kepala kerbau ini bukan sebuah jalan yang mudah. Butuh pendekatan yang luar biasa untuk jaman dimana tradisi masyarakat masih dipengaruhi oleh pengruh yang kuat dari Hindhu Budha. Namun pembelokan melalui natifisasi telah membelokkan perkembangan ini sehingga proses dakwah yang seharusnya berjalan justru berjalan stagnan dan generasi selanjutnya kehilangan sisi periwayatan ini.
Praktik mistik yang lain yang masih eksis di lereng Merapi adalah ritual telanjang yang dilakukan di Candi Lumbung pada setiap awal bulan Suro. Ritus ini dilakukan tengah malam selepas pukul 00.00 WIB dengan bertelanjang bulat mengelilingi Candi Lumbung sambil membaca mantra-mantra khusus di bawah panduan seorang pemimpin upacara. (Liberty, 11-20/1/2008: 67). Ritual ini juga masih memiliki kemiripan sebagai sisa ritual Bhairawa Tantra. Di daerah sekitar Merapi bekas-bekas setra (tempat pengorbanan manusia dan area persetubuhan masal dalam ritus bairawa) yang lain juga dapat ditemukan. Sampai sekitar tahun 2006, tempat pemujaan berupa Setra masih dapat ditemui di Bon Bimo. Namun di tempat petilasan itu saat ini telah didirikan sebuah masjid oleh masyarakat setempat. Cerita yang beredar di masyarakat saat tempat itu hendak didirikan masjid, batu yang menjadi “altar” penyembelihan gadis perawan di Bon Bimo tersebut pada waktu malam mengeluarkan suara tangisan yang bisa didengarkan hampir oleh setiap penduduk sekitarnya. Namun masyarakat telah memilih Islam dan sebuah masjid berdiri atas kehendak warga desa di tempat itu.
KAPITALISASI INDUSTRI PARIWISATA
Tradisi seperti penanaman kepala kerbau atau binatang ternak lain ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan dakwah Islam. Perhelatan ritual ini saat ini hanya dilakukan oleh sebagian orang dan tidak jarang atas sponsor Pemerintah Daerah dengan motif “memeras kocek” wisatawan. Kyai Muhammad Solikhin, peneliti dan pamomong masyarakat Desa Pedut, Cepogo misalnya mencontohkan bahwa pada saat gempa 2006, masyarakat di desanya masih melakukan penyembelihan Kambing dan kepalanya ditanam di sejumlah perempatan desa. Namun dalam gempa tahun 2010 ini tradisi bersifat bairawi tersebut telah ditinggalkan. Ketika terjadi gempa, masyarakat lantas berlindung ke masjid. Nampaknya mitos keliru tentang Mbah Petruk dan ritual yang mengikutinya memang sengaja hendak dipelihara dan dilestarikan demi sebuah kepentingan.
Dengan berlindung dibalik slogan “kearifan lokal” pemerintah daerah setempat berupaya mengkomersialisasikan ritual yang sebenarnya mulai ditinggalkan tersebut. Dalam cara pandang ini kebudayaan dianggap sebagai sebuah bentuk stagnasi sebuah periode sejarah. Kebudayaan ditempatkan sebagai obyek mati yang tidak bersifat dinamis dalam merespon perkembangan kebudayaan manusia. Komersialisasi demikian hakikatnya adalah pengembangan budaya bertopeng kapitalisme yang bergerak sebagai “monster” dalam ranah penghancuran kearifan lokal sebenarnya. Di satu sisi mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, namun juga mengorbankan aspek moralitas dan mentalitas manusia yang menjadi modal utama menjalani kehidupan dalam sebuah tuntunan baik. Isu “kearifan lokal” bukan berarti mengangkat “kebudayaan asli” melainkan menempatkan kebudayaan pada sebuah pemberhentian sampai mengalami titik jenuh. Pandangan yang digunakan bukan lagi menggunakan gaya ketimuran, melainkan berdasarkan paham yang diimpor dari kacamata materialisme Barat dalam melihat timur. Padahal cara pandang ini sebenarnya sangat aneh sebab merupakan cara pandang lama yang telah banyak ditinggalkan. Anehnya, pola ini malah diamalkan diIndonesia pada hari ini. Van Peursen, pakar strategi kebudayaan, menyebutkan cara pandang terhadap kebudayaan hari ini telah bergeser, dimana setiap orang merupakan kekuatan pembentuk kebudayaan. (Van Peursen, 1976:12).
Terkait Mbah Petruk, sudah saatnya umat Islam melanjutkan perjuangannya yang belum selesai dan menanti sentuhan berkelanjutan. Dakwah adalah sebuah amanah dari risalah kenabian yang dibebankan pada pundak kita. Jadi, demi kepentingan apa pun, jangan pernah memfitnah Mbah Petruk. Selamat berjuang. Wallahu a’lam.
(Makalah ini disusun berdasarkan investigasi terhadap tradisi lesan yang berkembang dalam masyarakat Selo dan Cepogo dimana Mbah Petruk merupakan ulama yang paling banyak beraktivitas di kedua tempat ini dibandingkan di wilayah lain di sekitar lereng Merapi. Investigasi ini melibatkan tokoh masyarakat setempat diantaranya adalah Kyai Muhammad Solikhin, “pamomong” masyarakat Pedhut, Cepogo yang juga merupakan seorang peneliti dan penulis buku yang cukup produktif tentang kebudayaan Jawa).
Penulis: Susiyanto
(Peneliti Pusat Studi Peradaban Islam (PSPI) & Mahasiswa Pasca Sarjana Peradaban Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta)Sumber; www.susiyanto.wordpress.com




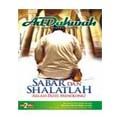

Tidak ada komentar:
Posting Komentar